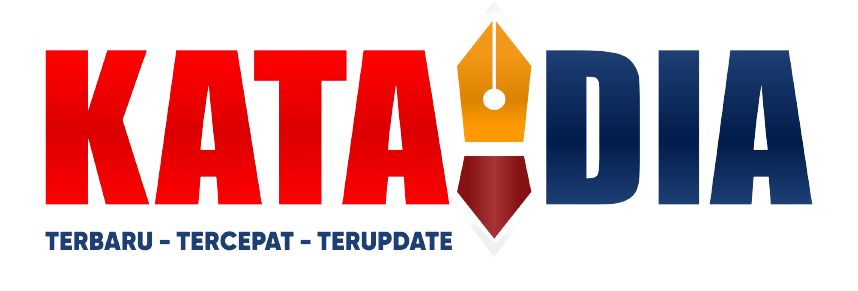Oleh: Rusdin Tompo*
(Koordinator Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA Provinsi Sulawesi Selatan)
Dunia kembali terhenyak. Rudal dan amunisi militer Israel membombardir Jalur Gaza. Hanya dalam tempo 3 pekan, tercatat lebih 7.000 korban tewas, di mana 66 persen di antaranya perempuan dan anak-anak. Demikian laporan Al Jazeera, yang menyampaikan imbas konflik bersenjata, yang pecah lagi sejak 7 Oktober 2023, di wilayah yang terletak antara Laut Tengah dan Sungai Yordan itu. Defense for Children International-Palestine (DCIP), bahkan secara tragis menyebut setiap 15 menit satu anak tewas. Agresi militer Israel tersebut segera membanjiri berbagai platform digital yang kemudian membentuk solidaritas di berbagai belahan bumi atas nama kemanusiaan.
Juru bicara UNICEF, James Elder, segera bereaksi mendorong urgensi penanganan cepat untuk melindungi anak-anak yang terancam di tengah konflik berkepanjangan tersebut. Anak-anak, menurutnya, merupakan kelompok paling rentan. Ia menilai, perang tersebut merupakan perang terhadap anak-anak. Sehingga, ia menyerukan semua pihak mengadvokasi perlindungan hak anak di zona konflik. Konflik militer-politik-agama antara Palestina-Israel, memang terbilang lama, terjadi sejak Abad XIX. Perseteruan panjang ini terus berlangsung bagai siklus kekerasan yang berulang hingga Abad XXI.
Dokumentasi Kekerasan
Human Rights Watch (HRW) menyebut sejumlah fakta anak-anak yang berada di medan konflik. Mereka mungkin berperang di garis depan, berpartisipasi dalam misi bunuh diri, dan bertindak sebagai mata-mata, pembawa pesan, atau pengintai. Banyak di antara mereka yang diculik atau direkrut secara paksa. Sementara yang lain bergabung lantaran putus asa karena percaya bahwa kelompok bersenjata menawarkan kesempatan terbaik bagi mereka untuk bertahan hidup (www.hrw.org). Namun, bagi anak-anak Palestina, ada semangat intifadah, mati syahid, sebagai bentuk perlawanan untuk memerdekakan tanah airnya.
Potret anak-anak Palestina yang berada dalam pendudukan Israel itu terekam secara baik dalam film-film dokumenter. Film “Born in Gaza” (2014), misalnya, menggambarkan pengepungan Gaza di tahun 2014 yang mengakibatkan 507 anak tewas dan 3.598 terluka. Dalam film dokumenter yang disutradarai Hernan Zin, terlihat anak-anak dipaksa dewasa sebelum waktunya. Kehidupan mereka keras, penuh teror. Mereka kehilangan ruang bermain yang aman dan tumbuh dalam ketiadaan makanan yang cukup. Meski begitu, anak-anak tak lagi punya rasa takut. Mereka bisa ‘hidup bebas’ dalam wilayah yang dikepung tentara Israel.
Film lain, berjudul “Two Kids a Day” (2022), mengisahkan anak-anak Palestina di Tepi Barat yang jadi tawanan Israel. Dalam film karya sineas Israel, Yoav Roeh dan Aurit Zamir itu, diungkapkan bahwa terdapat sekira 700 pemuda ditangkap militer Israel setiap tahunnya. Artinya, rata-rata dua anak setiap hari ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Perkaranya, mereka dituduh melempar batu tentara Israel, sehingga berakibat ditahan bertahun-tahun. Film yang menarik simpati ini, berhasil meraih penghargaan Grand Prix Japan Prize, yang disponsori NHK (Nippon Hoso Kyokai). Tentu saja, bukan semata-mata karena sinematografinya, melainkan menyingkap aspek kemanusiaan yang kuat.
Spiral Kekerasan
Fakta-fakta memiriskan diungkap UNICEF bahwa anak-anak Palestina mengalami kekerasan dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah, serta mengalami kekerasan domestik di rumah. Sebuah studi tentang kekerasan terhadap anak menyimpulkan ada dua sumber utama kekerasan. Pertama, kekerasan akibat pendudukan dan konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, dan kedua, kekerasan dalam keluarga dan komunitas Palestina. Kedua kekeransan ini saling berhubungan dan terkait dengan stres dan disfungsi keluarga (www.unicef.org).
Realitas hidup anak-anak Palestina ini mencerminkan apa yang disebut oleh Dom Helder Camara (1909-1999) sebagai spiral kekerasan. Teori ini dapat dijelaskan dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil, dan represi negara. Kemunculan kekerasan yang satu akan disusul dan memunculkan kekerasan lain, yang terus berulang. Anak-anak yang secara fisik, psikis, dan sosial tergantung pada orang dewasa, menjadi kelompok paling rentan dan berisiko. Berbagai paparan kekerasan yang dialaminya itu, juga mungkin akan ditiru dan diproduksi dalam skala dan intensitas berbeda.
Karena itu, hukum internasional menaruh perhatian besar terhadap nasib anak-anak, sesuai prinsip the best interest of the child. Keharusan memberikan perlindungan dan perlakuan manusiawi kepada anak-anak, sejatinya diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) PBB, tahun 1989, juga secara tegas mencantumkan hal ini. Bahkan ada Protokol Tambahan Konvensi Tentang Hak Anak Berkenaan Dengan Keterlibatan Anak Dalam Konflik-Konflik Bersenjata. Namun, napsu perang dan hasrat berkuasa, membuat kerangka hukum internasional sering tak berdaya di hadapan laras senjata dan moncong meriam.
Tampaknya, kita perlu merenungkan kata-kata James P. Grant dalam State of the World’s Children Report-1990, yang mengatakan bahwa sejak 1929 dunia disibukkan terus-menerus dengan perang, menghadapi perang, ancaman perang, menahan perang, mempersiapkan perang, dan membayar perang. Seluruh derita perang ini, paling berat dipikul oleh anak-anak kita. Kesejahteraan mereka dikurbankan, kesehatan mereka dihancurkan, dan masa depan mereka dirusakkan. []